Author: kathleen azali
-

Reportase: Membuat mainan di Akhir Pekan
Minggu sore, 17 Juli 2011, Nadhif, Ayesha, Revy, Firly dan Selvi berkumpul di ruangan perpustakaan C2O untuk mengikuti workshop Re – Make + Re – Use Toys. Dalam workshop ini, Heroes Ct, komunitas penggemar dan pembuat toys, dan Ayos Purwoaji memperagakan pengolahan dan pembuatan mainan dari barang-barang bekas seperti kardus, kancing, benang dengan menggunakan gunting…
-

Reportase: AeroSon, dunia paralel audio-visual
Kita mendengarkan musik sambil melihat wujud visualnya yang bergerak seiring. Dunia paralel audio-visual. *** Sabtu sore, 18 Juni 2011, pengunjung mulai berdatangan, menempati kursi-kursi yang telah disediakan, untuk menyaksikan pemutaran film AeroSon, musik grafik karya komponis Belanda, Arno Peeters. Dalam film ini, kita mendengarkan musik elektro-akustik sambil melihat visualisasinya. Sore itu, kami beruntung sekali dapat…
-

Reportase: Talkshow Garis Batas
Minggu, 15 Mei 2011, menjelang pukul 6 sore, pengunjung mulai berdatangan di C2O untuk acara bedah buku Garis Batas: Perjalanan di Negeri-negeri Asia Tengah. Cuaca sedikit mendung, gerimis turun rintik-rintik. Ajeng, moderator untuk malam ini, sudah siap semenjak 2 jam yang lalu. Dengan sedikit khawatir Rhea, koordinator GoodReads Surabaya, mengabari, “Mas Agus sakit, sepertinya datangnya…
-

Reportase: Book’s Day Out
Untuk memperingati Hari Buku Dunia pada tanggal 23, selama bulan April lalu kami merayakan Book’s Day Out dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan buku dan literasi. Di tahun pertama Book’s Day Out, kami memfokuskan pada sosialisasi dan peningkatan kesadaran akan keberadaan berbagai tempat literasi di Surabaya, serta pendekatan projek yang partisipatif and interaktif. Kami percaya…
-

Reportase: Bookworms’ Saturday
Sabtu, 9 April 2011, pk. 14.00-16.00, beberapa Bookworms berkumpul di C2O untuk membuat kartu pos bersama untuk projek Postcards from Bookworms, difasilitasi oleh Butawarna Design. Terkumpul berbagai kartu pos mengenai buku Botchan, The History of Java, Persepolis, dan lain sebagainya. Bagi yang tidak berkesempatan mengikuti workshop kali ini, silakan bergabung di workshop berikutnya Sabtu depan,…
-
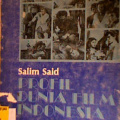
Profil Dunia Film Indonesia
Buku ini adalah salah satu buku sejarah film Indonesia yang paling populer dan mudah diakses, setidaknya di tahun 1980an. Berasal dari skripsi sarjananya, dalam buku ini Salim Said berusaha untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak dan kalangan yang mempersoalkan mutu dan kecenderungan utama (yang sering dikeluhkan dalam) film Indonesia. Misalnya, kenapa film Indonesia cenderung…
-
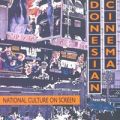
Indonesian Cinema
Dalam buku ini, film di sini diamati sebagai produk budaya, yang dapat dianalisa untuk mempelajari budaya asalnya (Indonesia). Menurut Heider, film-film Indonesia memiliki kharakteristik ke-“Indonesia”-an—sesuatu yang banyak diperdebatkan, mengingat banyaknya unsur daerah di Indonesia. Menurutnya, selain tidak adanya bisnis regional film, film-film Indonesia hampir semuanya menggunakan “bahasa Indonesia” (dengan sedikit frase-frase lokal sebagai bumbu) dan…
-

Report: Baca itu seru!
Sabtu, 12 Februari 2011, sekitar tengah hari, C2O kedatangan dua sahabat dari GoodReads Indonesia (GRI), Roos yang dulunya di GRI Jakarta, sekarang di Solo, dan Rhea Siswi, koordinator GRI Surabaya. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain datang, mereka mempersiapkan buku-buku untuk dipertukarkan (book swap) dan beberapa kaos dari penerbit untuk kopdar perdana GRI Surabaya siang nanti.…
-

Mati, Bertahun yang Lalu
Through the eyes of this walking dead, the novel details how life, fruitlessly clinging to the phantasmagoric promises of youth and happiness, becomes a big cosmic tragi-comedy.
-

Middlesex
An incestuous relationship between a pair of Greek siblings, consummated on a ship fleeing to the US from the Turkish raid at the beginning of the century, resulted in a pair of recessive genes finally reunited in a hermaphrodite of a grandchild (with a science geek turned John Lennon wannabe for an older brother).
-

Report: Jalan Raya Pos
Selama bulan November 2010, bekerja sama dengan komunitas Surabaya Tempo Dulu, kami memutar dua film berkaitan dengan sejarah Surabaya. Film ini diputar di C2O Sabtu lalu, 20 November 2010, dengan diskusi santai tapi informatif yang dipandu oleh dua admin komunitas Surabaya Tempo Dulu, Nikki Putrayana dan Ajeng Kusumawardani :). Sabtu, 20 November 2010, jam 17.30,…
-

Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma
Memuat kisah-kisah zaman Revolusi, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma dibagi secara kronologis menjadi tiga bagian: Jaman Jepang, Corat-Coret di Bawah Tanah, dan Sesudah 17 Agustus 1945. Dari buku yang tipis ini, kita dapat melihat semacam evolusi Idrus dari gaya romantik ke gaya khas satir tragikomiknya yang belum banyak dianut saat itu. Ringkas,…
